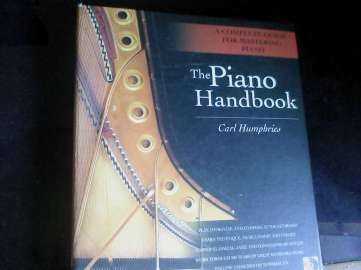Uncategorized
December 29, 2012
“Echo”
Album Surfing with the Alien (1987)
October 19, 2012
“In your eyes I find comfort and peace”
August 21, 2012
July 19, 2012
May 24, 2012
Philosophy of Technology (Blackwell Philosophy Guides) by Val Dusek – Powell’s Books
Posted by buzztanto under UncategorizedLeave a Comment
March 7, 2012
Oleh: Budi Hartanto
( peneliti filsafat teknologi)
Posfenomenologi adalah aliran dalam filsafat yang dikembangkan oleh Don Ihde seorang filsuf teknologi kontemporer. Sebuah filsafat yang menjelaskan tentang relasi pragmatis-eksistensialistis antara manusia sebagai tubuh dan dunia teknologi; yaitu ketika eksistensi manusia tidak lagi dapat kita maknai terbatas hanya pada tubuh dengan segala potensi panca inderanya saja, tapi juga berada pada moda relasi, mediasi, dan transparansi dengan teknologi. Posfenomenologi adalah pengembangan lebih lanjut fenomenologi Husserl dan khususnya fenomenologi Heidegger dan Maurice Merleu-Ponty.
Dalam filsafat Don Ihde dijelaskan bahwa fenomenologi tidak memadai untuk mengeksposisikan realitas masa kontemporer. Fenomenologi seperti kita ketahui adalah sains tentang fenomena yang hadir sebagaimana adanya. Ia sering dikatakan sebagai yang menengahi dua aliran besar filsafat modern: idealisme dan materialisme. Dengannya kita pahami secara eksistensial bahwa dunia-kehidupan adalah struktur relasional dan terberi antara manusia dan dunia. Secara intensional manusia sebagai ‘subyek atau ego’ mencerap dunia-kehidupan dalam kesehariannya, sehingga membentuk kesadaran tentang dunia dengan perspektif yang khas dan tersituasikan. Maurice Merleau-Ponty mengelaborasi fenomenologi tidak terbatas pada subyek tapi lebih pada relasi manusia sebagai ‘tubuh’ dengan dunianya. Ia berpendapat bahwa tubuhlah yang secara perseptual merasakan dan mengerti dunia. Don Ihde kemudian melengkapinya dengan menempatkan instrumen yang bersifat relasional sebagai ekstensi dari tubuh dalam memahami dunia. Dunia secara intensional dan perseptual mewujud lewat ‘instrumen’ atau teknologi. Pengalaman ditransformasikan oleh teknologi membentuk dunia yang sebelumnya tak dapat dipersepsikan.
Secara lebih luas sebenarnya posfenomenologi adalah filsafat material yang mensyaratkan setiap pengetahuan. Dalam keseharian ia menjadi moda dari cara mengadanya manusia di dunia. Instrumen telah mentransformasikan pengalaman manusia tentang dunia-kehidupan. Karena itu semua sains boleh dikatakan berada dalam aras posfenomenologi. Tidak hanya dalam penggunaan instrumen optik saja seperti dalam biologi molekular, fisika partikel dan kosmologi kontemporer, tapi juga geografi, antropologi, sejarah dan arkeologi yang mendasarkan pengetahuannya dengan mediasi material-material dalam sains dan teknologi. Dalam ilmu sejarah misalnya sumber material menjadi bagian penting untuk membaca sejarah selain sumber tekstual.
Don Ihde mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dengan posfenomenologi filsafat tidak lagi berorientasi linguistik. Pikiran/jiwa sebagai cogito tidaklah menjadi keutamaan dalam konteks penyingkapan ilmu pengetahuan. Kendati demikian bukan berarti sains kemudian menafikan rasionalitas, melainkan secara faktual ia berpijak pada kualitas-kualitas yang termanifestasikan secara instrumental-fenomenologis. Ia misalnya merumuskan gagasan tentang hermeneutika material. Menurut Don Ihde karena aktivitas sains pada dasarnya adalah bersifat sosio-kultural dan persepsional, hermeneutika material diperlukan dalam setiap penelitian sains. Karena itu menurut Don Ihde pemilahan analitis antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam tidak diperlukan karena keduanya sama-sama mengandaikan kegiatan hermeneutis (2003: hal. 18).
Ilustrasi posfenomenologi atau fenomenologi instrumentasi:
Manusia—teknologi/instrumen—Dunia {Pragmatis}
(Manusia— Intrumen/teknologi)—Dunia {Transparan}
Manusia—(teknologi/instrumen—Dunia) {Hermeneutis}
Dari ilustrasi di atas saya akan menjelaskan bagaimana teknologi secara pragmatis dimengerti sebagai bagian dari cara mengadanya manusia di dunia. Seperti kita ketahui relasi manusia—teknologi—dunia adalah menjadi pendasaran sains dan rasionalitas. Karena itu saya kira posfenomenologi menjadi penting dipahami.
Pembacaan realitas dengan dan melalui instrumen atau teknologi merupakan inti dari fenomenologi instrumentasi atau dalam konteks lebih luas posfenomenologi (1979: division one). Dalam filsafat Don Ihde kesatuan relasional inilah yang membentuk dunia-kehidupan secara perseptual. Ia misalnya memberikan contoh tentang penggunaan telepon (1979: hal. 23). Telepon merupakan instrumen yang menghadirkan dunia. Suara mewujud secara konstitutif sebagai dunia teknologis. Manusia sebagai keseluruhan tubuh tereduksi terbatas pada satu kualitas inderawi yang termediasikan oleh instrumen. Secara intensional dan parsial dunia mewujud sebagai dunia teknologi. Demikian pula astronom yang menggunakan teleskop untuk mengetahui rahasia-rahasia alam semesta. Teleskop dalam arti tertentu menjadi ekstensi dari tubuh, kesatuan relasional astronom—teleskop—dunia kemudian mencipta dunia secara partikular fenomenologis. Teleskop tidak hadir sebagai yang lain melainkan inheren sebagai tubuh itu sendiri, seolah-olah tubuh (mata) kita meluas dan melihat bintang-bintang dan planet-planet dari jarak dekat. Don Ihde mengistilahkannya sebagai transparansi dengan teknologi (1979: hal. 8). Yaitu ketika tidak lagi disadari keberadaannya sebagai yang lain melainkan bagian dari tubuh.
Atau contoh lainnya adalah thermometer yang digunakan untuk mengetahui kadar suhu yang tidak bisa dipersepsikan oleh tubuh. Penggunaan thermometer mengandaikan adanya kegiatan hermeneutis. Instrumen dalam hal ini mewujud sebagai yang lain yang terpisah dengan tubuh yang digunakan untuk membaca realitas. Don Ihde menyebutnya sebagai relasi hermeneutis dengan teknologi (1979: hal. 12). Relasi hermeneutis mengandaikan instrumen sebagai representasi realitas. Tubuh membaca dunia lewat teknologi sebagai yang lain.
Relasi manusia—instrumen—dunia membentuk secara perseptual sebuah rasionalitas tentang dunia-kehidupan. Namun bukan berarti posfenomenologi kemudian menafikan realitas sosial. Karena dalam keseharian kita temukan dunia posfenomenologis yang menjadi medium simetri sosial. Dunia yang direpresentasikan, tentu saja, tidaklah hanya realitas non-human tapi juga realitas sosial. Relasi instrumental yang tercipta adalah juga antara manusia sebagai tubuh dengan manusia-manusia lainnya sebagai realitas yang termediasikan. Pengalaman ditransformasikan dan tereduksi pada kualitas-kualitas inderawi tertentu, dunia-kehidupan tercipta secara instrumental-fenomenologis.
Kematian Posfenomenologis
Membahas kematian adalah selalu merujuk pada gagasan tentang terlepasnya jiwa (res cogitan) dari tubuh (res extenza). Inilah problem klasik dualisme jiwa-tubuh Cartesian. Eksistensi tak akan ada tanpa jiwa/pikiran dan tanpanya adalah juga sama dengan kematian. Filsafat Descartes sebenarnya menegaskan apa yang diwariskan oleh agama-agama dan tradisi kebudayaan tentang keberadaan jiwa sebagai entitas non-fisik yang tak terjelaskan. Keberadaannya dianalogikan seperti hantu di dalam mesin.
Seperti juga dalam fenomenologi awal sebenarnya masih dipercaya adanya ego/kesadaran sebagai pusat eksistensi. Dalam filsafat Husserl misalnya eksistensi tidaklah hadir sebagai sesuatu yang material. Fenomenologi Husserl dalam arti tertentu masih berada dalam bayang-bayang filsafat Descartes. Baru dalam fenomenologi yang dikembangkan oleh Maurice Merleau-Ponty tubuh mendapat tempat utama dalam membentuk persepsi tentang dunia-kehidupan. Dalam fenomenologi, pikiran atau jiwa yang dipercaya sebagai eksistensi memang tidak mendeterminasi cara kita melihat dunia, bahkan dalam perkembangannya yaitu dalam posfenomenologi tidak dikenal terma jiwa sebagai entitas nonfisik. Pemahaman kita tentang entitas yang dinamakan jiwa atau kesadaran secara keseluruhan adalah bersifat material atau atomistik. Tubuh yang tersituasikan dan bersifat relasional dengan instrumen yang menentukan bagaimana dunia itu hadir secara perseptual inderawi. Oleh karena itu kematian dalam posfenomenologi adalah selalu kematian tubuh dan relasinya dengan instrumen.
Lalu pertanyaannya adalah bagaimana posfenomenologi melihat kematian dan kematian eksistensial seperti dalam pemikiran Muhammad Damm? Kematian menurut Damm pada dasarnya dapat dipahami sebagai konstruksi sosio-kultural. Sehingga terbentuk sebuah antinomi antara kematian tubuh sosial dan tubuh korporeal. Di satu sisi tubuh bersifat organis korporeal, namun di sisi yang lain ia hadir sebagai eksistensi di tengah sosialitas. Bila kita lihat dalam sejarah filsafat eksistensialisme ketegangan antara tubuh sosial dan tubuh korporeal pernah dijelaskan oleh Gabriel Marcel dalam bukunya Being and Having (1949). Menurutnya ada kesatuan relasional antara aku sebagai ada yang bersifat sosial (being) dan tubuhku yang korporeal (having). Ada menurut Gabriel Marcel dapat dijelaskan lewat pernyataan eksistensialistik bahwa aku memiliki tubuhku. Jadi bila tubuh korporeal tidak dimiliki maka tidak ada aku sebagai subyek atau tubuh sosial. Aku menjadi ada sebagai yang terlepas dari tubuh, namun pada saat yang sama aku dan tubuh dapat menjadi kesatuan, misalnya ketika kita merasakan sakit pada tubuh kita. Proposisi aku memiliki tubuhku dalam filsafat Gabriel Marcel menerangkan bahwa manusia adalah tubuhnya sekaligus bukan tubuhnya, yaitu ketika tubuh dikatakan dimiliki oleh aku sebagai entitas yang tak dapat terjelaskan.
Dalam aras posfenomenologi kesadaran tentang kehidupan yang terangkum dalam tubuh dapat dipahami sebatas persepsi saja. Jadi selain kualitas inderawi yang dapat kita cerap secara langsung, juga dipercaya adanya persepsi yang membentuk kesadaran tentang dunia-kehidupan. Maurice Merleau-Ponty misalnya mengelaborasi fenomenologi tentang persepsi ini ke dalam realitas sosial. Kesadaran menurutnya adalah terbentuk secara fenomenologis lewat pengalaman mencerap dunia-kehidupan. Eksistensi tercipta berdasar pengalaman kemenubuhan (embodiment) yang berkembang secara perseptual-fenomenologis. Ia menjadi prasyarat terbentuknya realitas sosial. Kendati demikian bukan berarti kesadaran terbatas pada pengalaman yang asali saja, karena realitas sosial seperti kita ketahui membentuk banyak kualitas-kualitas kemanusiaan. Dalam filsafat Merleau-Ponty dijelaskan bahwa fenomenologi adalah juga mencakup nilai-nilai sosialitas manusia, seperti etika, politik, estetika, sejarah dan bahasa.
Ini tentu berbeda dengan filsafat Don Ihde yaitu bahwa eksistensi tidak terbatas pada tubuh dan potensi sosial-politisnya saja tapi juga instrumen atau teknologi. Secara pragmatis persepsi dapat dihadirkan dengan mediasi instrumen, karena itu apa yang kita ketahui sebagai kesadaran/pikiran dalam pemikirannya adalah tidak terpisah dari realitas material. Ia membuat terma mikropersepsi dan makropersepsi yang dengannya dunia-kehidupan mewujud sebagaimana adanya. Mikropersepsi adalah persepsi (materialis) yang hadir ketika kita mengenali kualitas-kualitas inderawi secara langsung. Sedangkan makropersepsi terbentuk secara sosio-kultural dan tidak bersifat langsung. Kepercayaan kita tentang adanya ceruk kawah dan gunung di bulan misalnya adalah makropersepsi yang terbentuk berdasarkan instrumen teknologis.
Dapat diproposisikan bahwa kematian eksistensial (tubuh sosial dan tubuh korporeal) dapat kita lihat secara persepsional, terutama dalam konteks makropersepsi yang dalam beberapa hal juga mengkonstruksi gagasan tentang kedirian atau eksistensi. Bahkan gagasan tentang mikropersepsi (yaitu ketika tubuh mencerap dunia) sebenarnya menjelaskan bahwa tubuh korporeal tidaklah benar-benar impersonal. Artinya tubuh dapat mengenali dunia inderawi (kepadatan, warna, suara, suhu) terlepas dari eksistensi tubuh sosial. Dikotomi tubuh sosial dan tubuh korporeal berkenaan dengan kematian seperti dirumuskan oleh Muhammad Damm sebenarnya dapat kita terangkan lewat fenomenologi persepsi dan instrumentasi ini.
Makropersepsi yang membentuk kesadaran adalah tentu saja tidak bisa dikonstitusikan sebagai dunia-kehidupan sebenarnya. Karena relasi tubuh, instrumen dan dunia secara pragmatis dan aktual mengandaikan terciptanya dimensi-dimensi kehidupan, makropersepsi tidaklah menjadi keutamaan dalam situasi relasional ini atau bahkan boleh dibilang tak ada. Konsekuensinya kematian dalam posfenomenologi bersifat korporeal dan instrumental. Eksistensi bukanlah state of mind Cartesian, melainkan inheren sebagai tubuh dan relasinya dengan instrumen.
Karena kematian universal adalah negativitas atas kehidupan (atau antifenomenologi), lenyapnya kehidupan yang dimediasikan oleh instrumen teknologis dapat dianalogikan sebagai kematian partikular-posfenomenologis. Kematian menjadi bersifat partikular sebagai konsekuensi berekstensinya dunia-kehidupan. Karena pengandaiannya, tentu saja, tubuh kita masih hidup, hanya kualitas yang bersifat relasional dengan instrumen yang diketahui sebagai mati. Terputusnya kehidupan virtual (simulasi komputer dan media sosial) dapat kita katakan sebagai kematian partikular. Simulasi tubuh virtual, yaitu tubuh yang berada dalam ruang virtual atau ketika tubuh diattach dengan kabel ke dalam komputer, menerangkan apa yang kita mengerti sebagai kematian partikular-posfenomenologis. Ketika realitas terputus itulah kematian partikular-posfenomenologis.
Kematian partikular-posfenomenologis menjadi lebih terasa dan terlihat dalam relasi manusia dan dunia sosial yang tercipta secara teknologis atau lebih spesifik media sosial (jejaring sosial). Mungkin inilah relevansi istilah kematian ‘tubuh sosial’ seperti dijelaskan oleh Muhammad Damm. Bahwa kematian selalu terkait dengan simetri sosial, bersifat intersubyektif, relasi manusia sebagai tubuh dengan manusia-manusia lainnya. Tanpa dunia sosial mungkin kematian menjadi tidak bermakna. Dimensi ‘afektif’ dari kematian sebenarnya dapat dijelaskan dalam konteks ini. Ketika memutus secara elektronis dan permanen seakan-akan kita merasakan kematian, kita tidak bisa hidup kembali di dunia teknologi. Dari sini dapat dimengerti bahwa kematian selalu menakutkan, selain rasa sakit tentunya, adalah karena terputusnya simetri sosial. Seseorang tidak ingin ditinggal dan meninggalkan realitas sosial. Seperti dalam nalar filsafat Heideggerian, eksistensi dalam arti being-towards-death bermakna ketika ada yang lain mati meninggalkan kita.
Namun perlu juga kita garisbawahi bahwa realitas sosial adalah selalu tersituasikan dan termediasikan oleh tubuh dan teknologi. Sebelum simetri sosial terbentuk pengandaiannya manusia sebagai tubuh mesti terlebih dulu secara inderawi dan instrumental mengenali dunia-kehidupan. Kita tentunya tidak bisa menafikan realitas yang asali ini. Karena tanpanya tak ada ruang sosial, pengenalan terhadap realitas menjadi syarat terciptanya sosialitas.
Fantasi Imortalitas
Lalu tentang imortalitas. Bagaimana hal ini dapat dipahami dalam konteks posfenomenologi dan kematian partikular? Imortalitas adalah keadaan tanpa kematian pada manusia. Kemungkinan imortalitas tentu hanya mungkin dalam hal pikiran/state of mind saja. Saya kira adalah jelas bahwa tak ada tubuh atau kehidupan yang abadi di bumi ini, semua kehidupan adalah pasti mati. Karena itu dalam kamus posfenomenologi tak ada kata keabadian/imortalitas. Diskursus filsafat tentang keabadian alam yang bermula sejak Aristoteles dan terus menggejala sampai periode filsafat Islam (Alfarabi dan Ibnu Sina) misalnya mendapat tanggapan yang cukup sengit dari Algazhali. Menurut Alghazali keabadian hanya ada pada Tuhan sebagai sebab dunia yang tidak abadi. Demikian pula saya kira sains kontemporer memberi penjelasan bahwa alam semesta pasti berakhir.
Dalam buku Muhammad Damm dijelaskan tentang filsafat imortalitas; ketika secara teknis dan ilmiah dimungkinkan terciptanya eksistensi yang dapat hidup imortal. Seperti misal pikiran yang diupload ke dalam komputer atau dipindahkan ke tubuh yang lain. Sehingga aku sebagai pikiran (state of mind) dapat hidup imortal. Bila kita telaah secara posfenomenologis hal ini sebenarnya hal ini tidak dimungkinkan. Kehidupan selalu mengandaikan keberadaan tubuh dan relasinya dengan teknologi. Robot atau instrumen hanya dapat kita kendalikan secara parsial lewat tubuh. Pemindahan pikiran sebagai eksistensi adalah ‘teknofantasi’ (2001: hal. 13). Karena pemindahan pikiran analoginya adalah membuat kesadaran dengan segala kompleksitas tubuhnya, imortalitas menjadi tidak rasional. Adalah wajar banyak ilmuwan menemukan jalan buntu berkenaan dengan kemungkinan-kemungkinan pemindahan jiwa/pikiran.
Berbicara tentang kehidupan (dan kematian) biasanya adalah selalu merujuk pada sekumpulan sel-sel dan organisme. Dalam posfenomenologi kualitas-kualitas yang kita pahami sebagai kehidupan organis sebenarnya dapat berekstensi secara teknologis. Kehidupan tidak hanya terbatas pada sel-sel dan organisme saja tapi juga bersifat ‘elektronis’ dan instrumental. Bahkan tidak hanya sistem relasional posfenomenologis, transplantasi organ tubuh dengan organ buatan/instrumen misalnya menjelaskan bahwa tubuh dan instrumen dapat menjadi kesatuan. Donna Haraway mengatakan dalam Cyborg Manifesto (1991) bahwa kita sekarang hidup dalam dunia cyborg (organisme sibernetis) yaitu sebuah dunia ketika tidak ada lagi batas-batas antara tubuh sebagai organisme dan teknologi. Artinya dalam pemikiran Haraway transparansi manusia dan teknologi dalam arti tertentu telah menjadi kenyataan, realitas tidak lagi termediasikan, manusia adalah cyborg.
Renungan-renungan atas kematian saya kira adalah penting diketengahkan agar ia menjadi rasional, tidak tabu dan menakutkan. Tema yang disampaikan dalam buku Kematian: Sebuah Risalah tentang Eksistensi dan Ketiadaan (2011) saya kira relevan dengan kondisi zaman dan searah dengan tujuan ilmu pengetahuan yaitu menyingkap yang tak terjelaskan seperti kematian.•
Referensi
Ihde, Don (2009). Postphenomenology and Technoscience. Peking University Lecture. SUNY Series of the philosophy of the social sciences . State University of New York Press.
———— (1979). Technics and Praxis. Boston Studies of Philosophy of Science. D. Reidel Publishing Company, Holland.
———— (2002). Bodies in Technology. Electronic Mediations; V. 5. Minneapolis: University of
Minnesota Press.
———— (2003). Postphenomenology—Again?. Working paper from centre of STS studies no. 3, University of Aarhus.
Haraway, Donna (1991). A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York, Routledge.
Heidegger, Martin (1973). Being and Time. Diterjemahkan oleh John Macquarrie & Edward Robinson. Oxford Basil Blackwell.
Marcel, Gabriel (1949). Being and Having. Harper & Row Publisher, New York.
Verbeek, Peter-Paul (2000). WhatThingsDo: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design. Diterjemahkan dari Bahasa Belanda oleh Robert P. Crease. The Pennsylvania State University Press University Park, Pennsylvania.
Merleau-Ponty, Maurice (1974) Phenomenology, Language and Sociology: Selected
Essays of Merleau-Ponty. Edited by John O’Neill. London: Heinemann.
Damm, Mohammad (2011). Kematian: Sebuah Risalah tentang Eksistensi dan Ketiadaan. Penerbit Kepik, Depok.
Hartanto, Budi (2004). Tentang Kematian dan Sifat-Sifat Jiwa. Dalam jurnal filsafat Driyarkara edisi Tuhan yang Tak Pernah Mati, TH. XXVII No. 2, Jakarta.
———— (2004). “Aku Mencerap maka Aku Ada” Koran Tempo Minggu, 18 April 2004, Jakarta.
Sunaryo (2006). Kritik Al-Gazhali atas Konsep Keabadian Alam Aristoteles. Dalam Jurnal Filsafat Driyarkara edisi Wacana Perempuan Th. XXVIII No. 3/2006.
Driyarkara SJ, N. (1989). Pertjikan Filsafat, Penerbit PT Pembangunan Jakarta.
February 2, 2012
Resensi Buku
Judul buku: Kematian: Sebuah Risalah Tentang Eksistensi dan Ketiadaan
Penulis: Muhammad Damm
Penyunting: Geger Riyanto
Penerbit Kepik. Depok
Jumlah halaman: 124
November 2011
Menelaah Kematian Eksistensial
Oleh: Budi Hartanto
Buku karya Muhammad Damm ini membahas konsep kematian dalam bingkai filsafat manusia. Membahas kematian biasanya memang tabu, sakral dan menakutkan, namun dengan gaya bahasa filsafat popular Muhammad Damm membuat kematian menjadi sesuatu yang biasa dan tidak menakutkan. Argumen-argumen dikemukakan dengan mengacu pada realitas sosial tanpa mengurangi kedalaman pemikirannya.
Kematian menurut Muhammad Damm pada dasarnya dapat dipahami sebagai konstruksi sosio-kultural. Ia secara filosofis membedakan kematian tubuh sosial dengan tubuh korporeal atau tubuh sebagai sekumpulan sel-sel atau organisme yang mensyaratkan kehidupan. Seseorang dapat dikatakan mati ketika tubuh sosialnya tak lagi dapat berinteraksi. Namun dalam tataran sel-sel dan tubuh sebagai organisme belum tentu seseorang dikatakan mati. Inilah menurutnya ambiguitas yang kemudian muncul ketika mendefinisikan kematian.
Dengan merujuk pada pemikiran Steven Luper dalam karyanya Philosophy of Death (2009) kematian dijelaskan oleh Muhammad Damm menjadi tiga bentuk berakhirnya kehidupan manusia. Yang pertama adalah kematian yang dipahami sebagai penyelesaian dari proses sekarat, ia menyebutnya (denouement death). Kedua kematian dipahami sebagai awal dari proses sekarat, yaitu ketika tidak lagi ada harapan untuk hidup (treshhold death). Yang terakhir adalah hilangnya kemampuan organisme untuk mengintegrasikan fungsi tubuh manusia (integration death). Dari tiga bentuk kematian ini ia kemudian mengajukan gagasan tentang kematian eksistensial. (2011, hal. 44-45).
Kematian eksistensial membentuk sebuah proposisi bahwa seseorang dapat dikatakan ‘hidup tapi mati’, yaitu ketika secara definitif tak ada lagi batas-batas antara hidup dan mati. Teknologi bidang medis dan kedokteran misalnya menjelaskan fenomena ini. Dengan bantuan teknologi tubuh korporeal dapat tetap hidup. Demikian pula orang yang hilang tubuh atau jasadnya. Secara sosial boleh jadi ia masih hidup, namun ketiadaan tubuh korporealnya dapat membuatnya dikatakan mati. Dengannya kita pahami bahwa pikiran atau jiwa tidaklah terbatas pada tubuh, tapi lebih luas dari itu, ia termanifestasikan ke dalam cakrawala eksistensi sebagai realitas sosial. Gagasan kematian eksistensial kemudian mendekonstruksi kematian sebagai negativitas; yaitu momentum ketika lenyapnya dunia-kehidupan individu sebagai tubuh sosial sekaligus tubuh korporeal.
Walaupun menjelaskan banyak hal berkenaan dengan kematian menurut saya buku ini belum cukup memberikan penjelasan perihal misteri kematian. Kehidupan setelah kematian misalnya menjadi rasional hanya dari perspektif agama-agama saja. Dan ia terkait dengan eksistensi jiwa atau ruh sebagai variabel dari ‘dunia-kehidupan’ itu sendiri. Menjelaskan kematian memang akan berakhir pada gagasan tentang kematian sebagai obyek pengetahuan; dalam konteks ini adalah ketika terlepasnya entitas yang dinamakan jiwa atau ruh. Ini saya pikir sama saja dengan sejarah sains dan filsafat yang dipahami sebagai aktifitas mengungkap rahasia-rahasia alam semesta.
Namun demikian Muhammad Damm dengan baik mensiasatinya dengan menjelaskan kematian sebagai sesuatu yang bersifat eksistensialistik. Kematian adalah state of mind yang hanya dirasakan oleh eksistensi sebagai the Other seperti tersebut dalam pemikiran filsafat Emmanuel Levinas. Dalam konteks inilah kematian secara filosofis menjadi tak terdefinisikan.
Sebagai sebuah refleksi filsafat buku ini menarik dibaca. Pemikirannya lugas dan ringkas. Saya kira pas untuk orang-orang yang terlalu sibuk membaca sebuah karya filsafat. Tema yang disampaikan juga relevan dengan kondisi politik dunia yang selalu mengabarkan kematian.•
December 29, 2010
Fasting and the Human Mind
Science Journalists
Journal of Young Investigators, March 2009
As a spiritual practice, fasting has been employed by many religious groups since ancient times. Historically, ancient Egyptians, Greeks, Babylonians, and Mongolians believed that fasting was a healthy ritual that could detoxify the body and purify the mind. In the modern era, three major religions in the world also advise fasting at certain times:, such as Judiasm during Yom Kippur, Christianity during the Lent period, and Islam during the festival of Ramadhan. Their beliefs are that fasting is a way to communicate with the Divine Being through the purification of the body and mind. The other major religions, such as Budhism and Hinduism also highly recommend this practice. In addition, the Natives Americans of Mexico and the Incas of Peru also observed fasting as the form of penance to their gods. Thus, throughout history, fasting has always been observed as a form of mind purification with a spiritual or religious intention and the act connotes spirituality.
This relationship is an abstract idea constructed by our collective historical experiences. Some fasting observers report that they have a sharper and more focused mind when they fast. But what do they mean? Is fasting truly mind-purifying?
Scientific realm defines the mind as cognition. It comprises of mental processes involved in gaining knowledge and comprehension, including thinking, knowing, remembering, judging, and problem solving. These are higher-level functions and encompass language, imagination, perception, and planning (Wagner 2009). Those functions are processed in the brain. The brain consists of billions of nerve cells. Just like other types of cells in the body, nerve cells need enough energy to work. This energy only comes from glucose. Therefore, to perform tasks such as memorization, the human brain needs sufficient glucose to meet its high energy demand.
Fasting is a condition when there is a temporary lack of glucose intake to the body. Glucose itself is the main fuel for the brain. Therefore it is logical to assume that humans have worse memory performance when fasting than when they are not.
However, evidence suggests that the lack of glucose while fasting does not hamper glucose availability in the brain. Our body is has v very sophisticated system of energy processing and has mechanisms to balance our physiological system via a process called homeostasis. So, when the body detects a lack of glucose, it tries to make glucose from other sources inside the body, such as glycogen and proteins. This new formation of glucose (gluconeogenesis) can balance glucose availability in the brain for 24 hours. This mechanism is also hard at work during day fasting, such as during Ramadhan.
In Indonesia, it is a common thing to hear that most Muslims attribute their lack of concentration at work to fasting. Workers are sanctioned fewer hours of work during Ramadhan for the same reason. Hunger is a sensation which indicates an empty stomach. It does not represent a lack of energy in the body. Hunger is a sensation that is processed in the brain and can be a distracting feeling. However, it is important to note that the sensation of hunger will only persist for short periods of time and will usually go away if we focus on other things.
Another interesting discourse about fasting is its spiritual phenomenon. Some religious people in the world state that they have visions while they are fasting and meditating. For example, some have had sensation of meeting God or achieving Nirvana. However, unlike Ramadhan, to achieve these states of being, severe fasting is often observed for a long period of time. Some people will not have meals for days or even weeks. Physiologically, this condition alters the body’s system of providing to the brain. While for short periods of fasting, the body can maintain energy availability by producing glucose from glycogen and proteins, during severe fasting, energy demands of the brain are fulfilled by ketone bodies. Ketone bodies yield energy in the form of ATP, which is used by nerve cells to maintain the membrane potentials needed to conduct electrical nerve impulses.
In comparison with glucose, ketone bodies are very good energy stores (Salway, 2004). One hundred grams of ketone bodies (hydroxybutyrate) can yield 10.5 kg ATP, which is a few times higher than the 8.7 kg of ATPs that can be produced from one hundred grams of glucose. Thus, it is reasonable to infer that the use of ketone bodies as the main fuel may produce different metabolic effects in the brain from the use of glucose.
For example, the different metabolism used in severe fasting may produce different mental processes, particularly in image perception. As implied in Hebb’s postulate, the molecular workings of nerve cells are the basis of mental processing. Nerve cells work to record and retrieve memory, manipulate information, think, imagine, and perceive the world. In addition, these cells function and perform these tasks through electrical impulses. Therefore, changes in electrical impulses which are produced by ketone bodies may produce different image perception compared with normal electrical impulses produced by glucose. This image could be something that the fasting observant has never experienced before.
This phenomenon can also be seen in some non-fasting situations, such as fatigue, epileptic seizure, or near-death situations, when patients claim to “see” images without any visual input. For example, some runners report that they scan “see” abnormal images after 30 to 40 minutes of running and many people often see “heaven” when they are near death (Mikami, 1997). The same phenomenon may happen in people who meditate while fasting for long periods of time. Most of them reportedly see divine images and may feel that their mind has been purified as a result of the experience.
However, despite these eyewitness accounts, there is still a lack of scientific evidence in the field of fasting. There are still many other areas other than physiological mechanisms, such as ketone metabolism and the sensation of hunger sensation, that need to be examined to determine the extent to which ideas such as mind purification and fasting can be linked. Currently, there are many cognitive areas of our mind that are still not completely understood to explain the many acts on spirituality that are happening in this world. Indeed, perhaps more attention needs to be paid to the intersection between human nature and science to a more concrete explanation to be found linking fasting and spirituality.
References
Mikami A. 1997. Possible neurophysiological basis of visual images seen in Shamanism. http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/brain/brain/102/discus_7.html
Salway JG. 2004. Metabolism at a glance. Oxford : Blackwell Publishing.
Wagner KV. 2009. What is cognition. http://psychology.about.com/od/cindex/g/def_cognition.htm
Written by: Guest contributor Dyna Rochmyaningsihh
Edited and published by: Hoi See Tsao